Bahasa Jawa Banyumasan
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read other articles:

Air warfare branch of Somalia's military Somali Air ForceCiidamada Cirka Soomaaliyeed/القوات الجوية الصوماليةCoat of arms of the Somali Air ForceFounded1960; 63 years ago (1960)Country SomaliaPart ofSomali Armed ForcesGarrison/HQAfsione, MogadishuMotto(s)Somali: Isku Tiirsada Lean TogetherEnsign Engagements 1964 Ethiopian–Somali Border War Shifta War Ogaden War 1982 Ethiopian–Somali Border War Somali Civil War CommandersCommander...

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) العراق تحت 17 سنة منتخب العراق تحت 17 سنة لكرة القدم معلومات عامة بلد الرياضة العراق الفئة كرة قدم تحت 17 سن...

Alfred T. Goshorn circa 1876 Trophy Vase presented to Alfred T. Goshorn, 1876 International Centennial Exposition Wikimedia Commons has media related to Alfred T. Goshorn. Alfred Traber Goshorn (July 15, 1833 – 1902) was a Cincinnati, Ohio businessman and booster who served as Director-General of the 1876 Centennial Exposition in Philadelphia. That was the first world's fair in the United States and so resounding a success that Queen Victoria knighted Goshorn and the leaders of Europe p...

Museo Etnográfico Juan Pérez VillamilUbicaciónPaís España EspañaComunidad Principado de Asturias Principado de AsturiasHistoria y gestiónCreación 2001[editar datos en Wikidata] El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil[1] es un museo perteneciente a la red de museos etnográficos de Asturias, España. El museo está situado en la localidad asturiana de Puerto de Vega, en el concejo de Navia. El museo inaugurado en 2001 partiendo de la iniciativa y trabajo d...

Pantai Ayah, adalah pantai yang terletak 8 km selatan Gua Jatijajar, 48 km dari Kota Karanganyar (Kedu) dan 63 km dari kota Kabupaten Kebumen, tepatnya di Desa/Kecamatan Ayah, merupakan objek wisata pantai yang memiliki keindahan alam sangat menawan. Dari kondisinya, yang berada di antara laut selatan dengan kawasan hutan jati milik Perum Perhutani KPH Kedu selatan ini, merupakan kombinasi atau perpaduan antara pantai dan hutan, seperti itu jarang kita jumpai. Untuk di jawa Ten...

Not to be confused with Canadian swimmer Stephen Clarke (swimmer). American swimmer Steve ClarkSchollander, Ilman, Austin and Clark display gold medals at 1964 OlympicsPersonal informationFull nameStephen Edward ClarkNicknameSteveNational teamUnited StatesBorn (1943-06-17) June 17, 1943 (age 80)Oakland, CaliforniaHeight5 ft 11 in (1.80 m)Weight148 lb (67 kg)SportSportSwimmingStrokesFreestyleClubSanta Clara Swim ClubCollege teamYale University Medal reco...

Android Smartphone For other uses of One plus one, see 1+1 (disambiguation). OnePlus OneThe front face view of the OnePlus One (Sandstone Black, 64 GB) running Cyanogen OS 12CodenameBacon[1]BrandOnePlusManufacturerOnePlusSloganNever Settle 2014 Flagship KillerModelA0001Compatible networksGSM, WCDMA, LTEFirst released23 April 2014; 9 years ago (2014-04-23)Availability by region25 April 2014 (Invite-only release) 6 June 2014 (Worldwide release) 2 December 2014 (India)&...

US pulp science fiction magazine Fantastic NovelsMary Gnaedinger continued to reprint work by A. Merritt in the second series of Fantastic Novels. (September 1948 issue pictured)EditorMary GnaedingerCategoriesScience fictionFantasyPulpFrequencyBimonthlyFounded1940Final issue1951CompanyMunsey CompanyPopular PublicationsCountryUnited StatesCanadaGreat BritainBased inNew York CityLanguageEnglish Fantastic Novels was an American science fiction and fantasy pulp magazine published by the Munsey Co...

Pour les articles homonymes, voir EPR. Le réacteur pressurisé européen ou EPR (initialement European pressurized reactor, renommé Evolutionary power reactor) est un réacteur nucléaire appartenant à la filière des réacteurs à eau pressurisée. C'est un réacteur de génération III, selon la classification internationale. Il s'agit d'un réacteur de forte puissance (~1 600 MWe) conçu dans les années 1990 par la co-entreprise franco-allemande NPI (Nuclear Power Internation...

2012 filmReversionDirected byGiancarlo NgWritten byGiancarlo NgStarringDaniela HummelMusic byDan EckertProductioncompanyThe Magic Movie MachineRelease date August 8, 2012 (2012-08-08) (online release) Running time11 minutesCountriesPhilippines and InternationalLanguageEnglish Reversion is a computer-animated short film directed by Giancarlo Ng and produced by The Magic Movie Machine, a self-described collaborative animation team. The 11-minute short film was created using B...

Italian naval officer (1911–1943) Saverio MarottaBorn(1911-09-04)4 September 1911Falconara Marittima, Marche, ItalyDied4 May 1943(1943-05-04) (aged 31)Mediterranean SeaAllegiance Kingdom of ItalyService/branch Regia MarinaYears of service1929–1943RankLieutenant CommanderCommands held Perseo (torpedo boat) Battles/wars Spanish Civil War World War II Battle of the Mediterranean Battle of the Campobasso Convoy Awards Gold Medal of Military Valor (posthumous) Silver Medal ...

第五代边疆伯爵和第七代阿尔斯特伯爵埃德蒙·莫蒂默边疆伯爵和阿尔斯特伯爵繼任第三代约克公爵理查出生(1391-11-06)1391年11月6日新森林,韦斯特米斯郡逝世1425年1月18日(1425歲—01—18)(33歲)特里姆城堡墓地克莱尔隐修院,萨福克家族莫蒂默配偶安妮·斯塔福德(1415年结婚—1425年結束)父親第四代邊疆伯爵羅傑·莫蒂默母親埃莉诺·霍兰 莫蒂默的纹章 第五代边疆伯爵、第七...

Main railroad station in Los Angeles, California Los Angeles Union Station The main building with tracks in the backgroundGeneral informationLocation800 North Alameda StreetLos Angeles, CaliforniaUnited StatesCoordinates34°03′19″N 118°14′07″W / 34.05515°N 118.23525°W / 34.05515; -118.23525Owned byLos Angeles County Metropolitan Transportation AuthorityPlatforms6 island platforms (Amtrak/Metrolink)1 island platform (Metro A Line)1 ...

You can help expand this article with text translated from the corresponding article in Vietnamese. (March 2009) Click [show] for important translation instructions. View a machine-translated version of the Vietnamese article. Machine translation, like DeepL or Google Translate, is a useful starting point for translations, but translators must revise errors as necessary and confirm that the translation is accurate, rather than simply copy-pasting machine-translated text into the English ...

Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini.Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala.Tag ini diberikan pada Oktober 2022. Orientasi data (Data onboarding) adalah proses mengirimkan data dari luar jaringan (luring) ke dalam jaringan (daring) sesuai kebutuhan pemasaran.[1][2] Orientasi data digunakan dengan menghubungkan catatan pelanggan luring dengan pengg...

Suburban One LeagueFormerlySuburban LeagueConferencePennsylvania Interscholastic Athletic Association (PIAA District 1)Founded1922Sports fielded 26 men's: 15 women's: 11 SubdivisionAmerican Conference Continental Conference National ConferenceNo. of teams24HeadquartersPennsylvaniaRegionMontgomery County (12 Schools)andBucks County (12 Schools)Official websiteSOL Website Suburban One League, often abbreviated SOL is an athletic conference in Southeastern Pennsylvania, serving high schools in M...

Indonesian independence activist (1908–1986) Abdurrahman Baswedanعبد الرحمن باسويدان2nd Deputy Minister of Information IndonesiaIn office2 October 1946 – 3 July 1947PresidentSukarnoPrime MinisterSutan SjahrirPreceded byAli SastroamidjojoSucceeded byPosition removed Personal detailsBorn(1908-09-09)9 September 1908Ampel, Soerabaja, Dutch East IndiesDied16 March 1986(1986-03-16) (aged 77)Jakarta, IndonesiaResting placeTaman Kusir CemeterySpouse(s)Sjaichun (...

Questa voce sull'argomento cestisti statunitensi è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. Jimmy Dan Conner Conner con la maglia di Kentucky Nazionalità Stati Uniti Altezza 193 cm Peso 86 kg Pallacanestro Ruolo Guardia Termine carriera 1976 Carriera Giovanili Anderson County High School1971-1975 Kentucky Wildcats Squadre di club 1975-1976 Kentucky Colonels24 Il simbolo → indica ...

Indian writer in the Telugu language (born 1953) This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these template messages) This biography of a living person needs additional citations for verification. Please help by adding reliable sources. Contentious material about living persons that is unsourced or poorly sourced must be removed immediately from the article and its talk page, especially if potentially libelou...
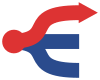
线路名消歧义 单字母 A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z 多字母 AK · BL · BR · CC · CD · CG · DT · GN · HC · HS · IY · JA · JB · JC · JE · JH · JI · JJ · JK · JO · JT · JU · KB · KD · KS · MR · NS · OR · SB · TT 颜色紅 · 粉紅 · 洋紅 · 橙 · 黃 · 金 · 棕 · 綠 · 淺綠 · 藍 · 淺藍 · 紫 · 灰 · 銀 编号(0~99)0 · 1 · 2...

